Inovasi penjarahan / perampasan aset secara paksa dirumah dewan dpr dan menteri dan ketua dewan RI,
Merupakan inovasi masyarakat terkait lambatnya pengesahan UUD perampasan aset oleh piphak DPR ri.
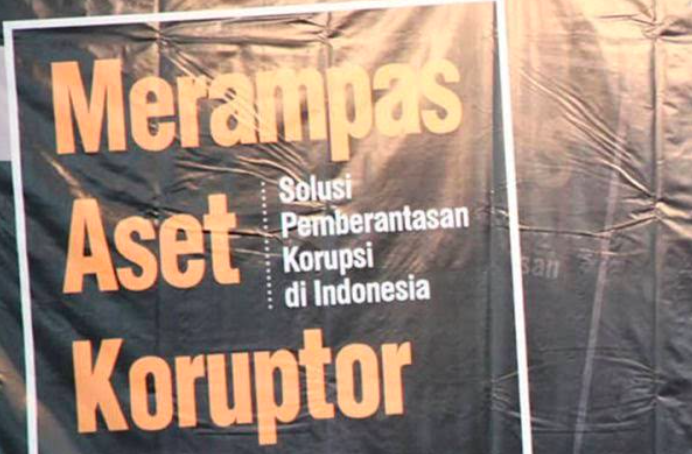
Baca juga : Mengenang Para Pahlawan Pejuang Reformasi 98
Baca juga : inovasi menaikan gajih tunjangan kesejahteraan DPR
Baca juga : Polri intitusi mengayomi rakyat tapi bohong!!
Baca juga : TRAGEDI1998 JILID 2 TAHUN 2025 #IND0NESIA GELAP
Baca juga : DEMO RAKYAT PAJAK RAKYAT NAIK ANGGARAN DPR IKUT NAIK
Fenomena perampasan aset oleh masyarakat bukan sekadar isu kriminalitas, melainkan potret nyata benturan antara hukum formal negara dengan realitas sosial dan kebutuhan hidup rakyat. Dalam terminologi hukum, hanya negara yang memiliki kewenangan merampas aset (misalnya melalui penyitaan aset koruptor, bandar narkoba, atau pelanggar hukum lain). Namun di lapangan, masyarakat sering mengambil alih lahan, properti, atau sumber daya yang dianggap mereka miliki secara historis maupun moral.
Tindakan ini menimbulkan dilema: secara hukum positif adalah pelanggaran, namun secara sosial sering dipandang sebagai perjuangan hak. Dalam dua dekade terakhir, konflik agraria dan okupasi lahan menjadi cermin nyata dari fenomena ini. Data menunjukkan bahwa Indonesia mengalami eskalasi konflik agraria terbesar di Asia (Konsorsium Pembaruan Agraria, 2024).
Konteks Hukum Formal
- Definisi Perampasan Aset
- Diatur dalam UU Tindak Pidana Korupsi, UU TPPU, dan KUHP.
- Hanya dapat dilakukan negara melalui proses pengadilan.
- Masyarakat sebagai Pelaku Perampasan Aset
- Jika mengambil alih tanah atau properti tanpa izin, dapat dikenakan Pasal 385 KUHP (penyerobotan tanah), Pasal 362 (pencurian), atau Pasal 170 (kerusuhan).
- Dari sudut pandang aparat, aksi ini masuk kategori tindak pidana.
- Kesenjangan Legitimasi
- Secara sosial, tindakan okupasi lahan dianggap sah oleh komunitas karena alasan historis (tanah adat), survival (tanah untuk bertani), atau protes terhadap ketidakadilan.
- Inilah benturan tajam: legalitas vs legitimasi.
Data Konflik Agraria: Fakta Lapangan Terkini
Menurut catatan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) dan ATR/BPN, konflik agraria terus meningkat. Berikut rangkuman data:
- 2024: 295 konflik agraria, naik 21% dari 241 konflik tahun 2023.
- Luas areal terdampak: 1,113,577 hektar.
- Jumlah keluarga terdampak: 67.436 KK di 349 desa.
- Sektor penyumbang terbesar:
- Perkebunan (111 kasus, dominasi sawit).
- Infrastruktur (79 kasus).
- Tambang (41 kasus).
- Kehutanan (25 kasus).
- Korban kekerasan: 556 orang, dengan 4 korban tewas (KPA, 2025).
- Pelaku kekerasan terbanyak: preman/perusahaan (148 kasus), polisi (129), Satpol PP (44), TNI (37).
ATR/BPN juga mencatat 5.973 konflik agraria pada 2024. Mayoritas konflik berskala rendah (warisan atau sengketa individu), tetapi terdapat 374 kasus besar masyarakat vs korporasi/negara, serta 47 kasus “political intensity” yang berpotensi memicu gejolak politik nasional.
Studi Kasus Lapangan
1. Rempang, Kepulauan Riau (2023–2024)
Ribuan warga menolak relokasi untuk pembangunan Eco City yang masuk Proyek Strategis Nasional (PSN). Warga melakukan blokade jalan, menduduki lahan, dan menolak penggusuran. Aparat menggunakan gas air mata; konflik ini menjadi sorotan internasional.
2. Kendeng, Jawa Tengah
Masyarakat menolak pabrik semen yang dianggap merusak sumber air. Aksi “semen kaki” di depan Istana Negara menjadi simbol perlawanan. Mereka mengklaim lahan pertanian sebagai sumber hidup yang tak tergantikan, meski negara memberi izin usaha tambang.
3. Mesuji, Lampung
Konflik tanah antara warga dengan perusahaan perkebunan sawit berujung bentrok berdarah pada 2011 dan masih meninggalkan trauma. Warga menduduki lahan yang mereka klaim sebagai tanah adat, meskipun perusahaan memiliki HGU.
4. Papua
Konflik antara masyarakat adat dengan konsesi sawit dan tambang Freeport. Warga seringkali melakukan aksi blokade atau menduduki area operasional. Dalam narasi adat, tanah adalah identitas dan “ibu” yang tidak bisa diperdagangkan.

Faktor Pemicu
- Ketimpangan Penguasaan Tanah
- Data BPS menunjukkan 1% penduduk menguasai lebih dari 50% lahan produktif.
- Konsesi HGU raksasa diberikan kepada korporasi, sementara petani kecil kekurangan lahan.
- Lemahnya Reforma Agraria
- Program redistribusi tanah berjalan lambat; hanya sebagian kecil target tercapai.
- Masyarakat frustasi lalu melakukan okupasi langsung.
- Hak Ulayat yang Diabaikan
- Putusan MK No. 35/2012 sudah menegaskan hutan adat bukan hutan negara, tetapi implementasinya minim.
- Proyek Strategis Nasional (PSN)
- Sejak 2020–2023, tercatat 115 konflik agraria akibat PSN. Tahun 2024 saja ada 36 kasus.
- Kriminalisasi & Represi
- Aparat sering lebih cepat menindak masyarakat daripada menertibkan perusahaan.
Dampak Perampasan Aset oleh Masyarakat
- Sosial
- Korban jiwa, kriminalisasi, trauma kolektif.
- Perpecahan sosial (pro dan kontra di antara warga).
- Politik
- Menurunkan legitimasi pemerintah.
- Menjadi isu politik lokal dan nasional.
- Ekonomi
- Investasi terhambat akibat konflik berkepanjangan.
- Namun bagi masyarakat, okupasi sering satu-satunya cara mempertahankan ekonomi keluarga.
- Hukum
- Menimbulkan paradoks hukum: masyarakat dianggap melawan hukum, sementara negara gagal melindungi hak mereka.

http://www.mstsgmo.com
Perspektif Teoritis
- Hukum Positif: perampasan aset hanya sah bila dilakukan negara.
- Teori Keadilan Sosial (John Rawls): masyarakat berhak menuntut distribusi adil atas sumber daya.
- Hukum Adat vs Hukum Negara: masyarakat adat menempatkan tanah sebagai hak kolektif, bukan komoditas.
- Teori Konflik (Karl Marx): perampasan aset masyarakat adalah akibat dominasi kelas pemilik modal atas kaum kecil.
Rekomendasi Solusi

- Percepatan Reforma Agraria
- Redistribusi tanah secara nyata, bukan sekadar sertifikasi.
- Pengakuan Formal Hak Ulayat
- Implementasikan Putusan MK 35/2012 dengan melibatkan masyarakat adat.
- Mediasi Tripartit
- Pemerintah, perusahaan, dan masyarakat duduk bersama dengan fasilitator independen.
- Transparansi Konsesi Lahan
- Publik berhak tahu siapa yang menguasai lahan dan untuk apa.
- Pendekatan Humanis
- Aparat tidak boleh menjadi alat pemukul, melainkan mediator.
- Revisi Regulasi PSN
- Wajib ada studi dampak sosial, bukan hanya dampak lingkungan.



